"... we need an
erotics of art" - Susan Sontag (1964).
Kemewahan yang
dimiliki oleh seorang pengajar adalah peluang untuk kembali (dan terus)
belajar. Kadang memang tentang hal yang sama sekali baru, atau dalam kasus saya
saat ini, tentang hal yang harus dipelajari ulang. Untuk persiapan materi
perkuliahan, saya sedang membaca essay lama Susan Sontag, “Against
Interpretation”, yang merupakan essay seminal untuk studi seni. Sudah lewat 10
tahun ketika saya pertama membaca essay ini untuk kuliah Sejarah Seni, dan saya
teringatkan kembali akan betapa handalnya Sontag sebagai penulis – substansi
memang terbilang berat, tapi ini diimbangi oleh gaya yang elegan dan mudah
dicerna. Samar-samar saya masih ingat argumentasi Sontag, meskipun tidak rinci,
dan saya ingat betapa relevannya point-point yang dikatakan Sontag untuk saya
waktu itu.
Sekarang, saya
merasa adanya pergeseran pada pengertian saya tentang isi essay Sontag.
Dulu sepertinya yang saya anggap paling adalah gema relativisme yang saya
kira saya tangkap dalam essay Sontag: bahwa pengertian akan karya seni itu
relatif, dan ‘interpretasi’ dalam artian yang pasti dan kekal sudah tidak bisa
diterapkan lagi. Terlebih saat mendengar filsuf sains Paul Feyerabend
("Against Method", 1975) mengatakan bahwa gagasan tentang adanya
metode yang 'pasti' itu naif, dan pada dasarnya hanya ada satu prinsip yang bisa
dipertahankan: "anything goes!" Pendek kata, semangat
‘pembebasan’ dari indoktrinasi yang mencirikan pemikiran postmodern – lewat
dalih relativisme – yang saya yakin pernah memukau banyak mahasiswa yang kalau
bukan seangkatan saya, masih dekat generasinya.
Tapi sekarang ada
hal lain dari essay ini yang menonjol bagi saya, terkait dengan kutipan diatas.
Intinya kira-kira begini: berhadapan dengan sebuah karya seni, ‘menentang
interpretasi’ adalah langkah penting untuk kembali ke ‘pengalaman’ akan karya
tersebut, dan tentunya disini saya mengatakan ‘pengalaman’ dalam arti
fenomenologis: ‘bertubuh’.
Menurut Sontag,
kesalahan utama pada teori-teori seni yang ada – Sontag menyebut mulai dari
filsafat seni Plato tentang seni sebagai ‘imitasi dari imitasi’ hingga
teori-teori modern yang terkenal seperti Marx dan Freud – adalah penekanan pada
apa yang Sontag sebut dengan ‘content’ atau isi: “... content still comes first”
(2). Sebagai akibat, karya kemudian dimengerti seakan-akan sebuah teks, dimana yang dimaksud
dengan interpretasi sebernarnya adalah penterjemahan: “Sang interpreter
mengatakan, Lihat, tidakkah anda bisa melihat bahwa X itu adalah – atau sebenarnya
adalah – A? Bahwa Y adalah B? Bahwa Z adalah C?” (5). Sebenarnya pandangan seperti ini, yang menganggap bahwa karya seni adalah sesuatu yang bisa
di’interpretasi’, mempunyai akar sejarah peradaban pada Pencerahan, ketika manusia sedang terpesona oleh kemampuannya untuk berlogika dan
bernalar secara pasti dan ‘realistis’. Masalahnya, bagi Sontag, adalah
interpretasi mengasumsikan adanya ketidaksesuaian atau kesenjangan antara
pembaca dan suatu makna karya yang ‘jelas’, ‘otentik’, ‘paling benar’. Selain itu, 'interpretasi' juga mengasumsikan bahwa suatu kemampuan bernalar belaka mampu meluruskan kesenjangan
itu (seakan-akan kesenjangan itu pada dasarnya ada).
Tak heran Sontag, di
awal essay, sempat membayangkan karya-karya seni pertama sebagai sesuatu yang
magis, magis karena tidak perlu dipertahankan oleh teori dan tafsir: andaikan
kita dapat kembali ke suatu waktu, tulis Sontag, “ketika seseorang tidak
menanyakan pada sebuah karya apa yang dibicarakannya,
karena ia tahu (atau merasa tahu) apa yang dilakukan karya itu.” (4-5) Bahkan
Sontag kemudian berkata bahwa “intepretasi itu memiskinkan... Karya seni sejati mempunyai
kapasitas untuk membuat kita gelisah. Dengan menciutkan sebuah karya menjadi
isinya dan kemudian menginterpretasikan itu, kita menjinakkan karya tersebut.
Interpretasi membuat sebuah karya gampang diatur, gampang tunduk”. (8)
Diakhir essay,
Sontag menuliskan frasa “an erotics of art”, tanpa penjelasan lebih
lanjut. Lengkapnya, dia mengatakan “In place of a hermeneutics we need an
erotics of art.” (14) Apa maksud Sontag dengan ini pernyataan ini? (Saya
menganggap Sontag menunjuk pada hermeneutics dalam artian tradisional, yaitu
sebuah ilmu yang secara khusus mempelajari bagaimana sebuah teks, misalnya teks
kuno tentang agama atau sastra, dapat diinterpretasi, dan bukan metode filsafat
hermenetik milik Heidegger atau Gadamer.) Disini, Sontag bukannya bermaksud
bahwa karya seni – apapun jenisnya – benar-benar tidak bisa dikata-katakan,
tidak bisa dideskripsikan (describe) atau dijelaskan kembali
(paraphrase). Tapi Sontag menanyakan, bagaimana cara kita melakukan itu
sekarang? (Sekarang dalam artian tahun 1964, saat essay ini ditulis.) Dia
menggagas ‘form’ dan ‘appearance’ (terjemahan harafiah: ‘bentuk’ dan
‘tampilan’) sebagai faktor-faktor paling mendasar untuk kritik seni, dan
memberikan contoh-contoh kritisisme yang justru TIDAK membahas isi dan lebih mempertimbangkan bentuk dan tampilan.
Rumpun kata
‘erotics’ berhubungan dengan dewa cinta Yunani (Eros), dan ini membentuk
pengertian modern kita tentang ‘erotics’ sebagai sesuatu yang merangsang suatu
bentuk cinta yang unik: badaniah. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa
erotisme itu hanya terbatas pada stimulan fisik; sama sekali tidak, karena ini
menggampangkan kompleksitas fenomenon ini. Tapi tidak bisa tidak, salah besar
apa bila kita menganggap bahwa erotisme adalah suatu peristiwa mental saja:
mereka yang mengklaim pernah merasakan terangsang oleh cinta ilahiahpun – yang disangka
bersifat spiritual – terlihat mengalaminya dengan tubuh mereka. Lihat patung
Santa Teresa disini, dalam keadaan ekstasi rohani:
Ketika dia merasakan ujung
tombak si malaikat menusuk hatinya, katanya: “The pain was so great, that it
made me moan; and yet so surpassing was the sweetness of this excessive pain,
that I could not wish to be rid of it. The soul is satisfied now with nothing
less than God. The pain is not bodily, but spiritual; though the body has its share in it.” (Thanks wiki, huruf miring
dari saya). Terlihat disini bahwa dalam erotisme religiuspun, tubuh tetap
berperan.
“An erotics of art” yang
Sontag sebut juga mengacu pada pengalaman indrawi atas karya seni, seperti yang
dia jabarkan dengan ‘form’ dan ‘appearance’. Dengan menggarisbawahi pengalaman
indrawi, Sontag berusaha menghindari interpretasi karena dua alasan: 1/ interpretasi
dianggap sebagai proses mental saja, dan 2/ meskipun manusia tidak bisa
mengelak dari interpretasi, interpretasi telah meng-institusi secara hierarkis
dan menghasilkan kubu-kubu penilaian seperti ‘benar’ dan ‘salah.
Meski Sontag tidak
mengatakan demikian, pernyataan-pernyataan yang dibuatnya menunjuk pada suatu
kelangsungan (immediacy) antara karya – dalam wujud fisiknya – dan orang yang berada
didepannya. Tapi yang disayangkan adalah langkah Sontag untuk ‘menentang’
interpretasi seluruhnya. Dia seakan melupakan bahwa manusia menginterpretasi
keadaan sekelilingnya, bukan lewat nalar saja, tapi juga melalui tubuhnya:
misalnya, jika suatu karya mempunyai ‘pesan’ apapun, ini tidak selalu saya
tafsirkan lewat daya pikiran, tapi lewat apa yang saya bisa lihat, dengar,
rasakan pada kulit, dan seterusnya, yang kemudian memancing berbagai imajinasi
dan pengkhayalan lebih lanjut. Sontag memang benar dalam mengingatkan kita akan
dominasi ‘isi’, ‘content’, ‘pesan’ dalam sebuah karya, tapi salah dalam
meneruskan dualisme Cartesian antara fisik dan mental, tubuh dan batin.
Mungkin disini yang saya
inginkan adalah semacam a return to
materiality. Tapi, bukan dalam artian materialitas ‘dingin’ yang meninggalkan
kompleksitas dan kedalaman rasa dan emosi, melainkan dalam bingkai ‘erotisme’
yang Sontag berikan. ‘Poetics’ atau ‘kepuitisan’ sering mempunyai predikat
buruk sebagai sesuatu yang ornamental, muluk-muluk dan bersifat embel-embel. Padahal
kalau kita mempertimbangkan istilah ini dalam artian kata Yunani Kuno poeisis – suatu langkah ‘revealing’ atau ‘penyingkapan’ – maka istilah ini sudah
tidak lagi bisa dianggap embel-embel saja, tapi menjadi sesuatu yang penting.
Ketika ‘poetics’ dipahami dalam artian ‘penyingkapan’, berarti suatu karya
mempunyai kekuatan untuk ‘menyingkapkan’ berbagai macam hal; bisa jadi hal yang
telah terlupakan, yang tidak diketahui sebelumnya, dst. Agar fundamentalitas ‘poetics’
tidak lagi tersingkirkan, mungkin kita harus kembali pada
materialitas karya itu sendiri, yang secara langsung melibatkan pengalaman 'bertubuh'.
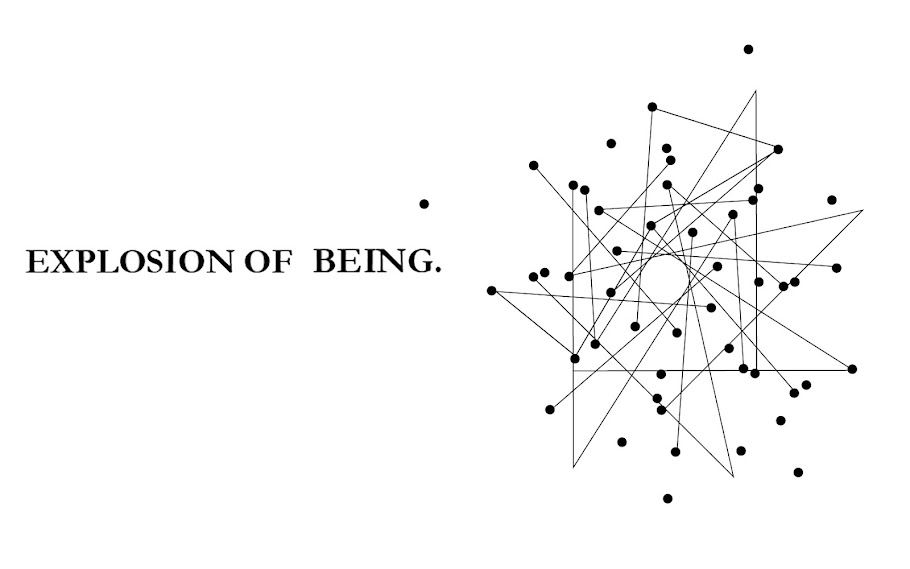

No comments:
Post a Comment